Batik motif Pekalongan adalah salah satu batik yang termasuk jenis klasik di Indonesia. Batik dari kota di Jawa Tengah ini sudah melampui perjalanan sejak abad 17.
Batik Motif Pekalongan
Pekalongan memang telah menjadi salah satu pusat produksi batik di Indonesia, ia juga dikenal sebagai Kota Batik. Sejarah batik Pekalongan bisa dirunut sejak abad 17, masa ini kerajinan batik mulai berkembang di sini.
Pada masa itu, batik motif Pekalongan popular sebagai kain yang dipakai sebagai pakaian formal dan upacara adat. Selama berabad-abad, motif-motif batik Pekalongan terus berkembang, mencerminkan pengaruh budaya lokal dan internasional.
Pekalongan merupakan kota di wilayah utara pulau Jawa dan berada di Provinsi Jawa Tengah. Dari Jakarta kota ini berjarak 384 kilometer, sedangkan dari Semarang jaraknya sekitar 100 kilometer.

Batik Pekalongan mencatat adanya pengaruh kebudayaan dari masyarakat sekitar yang selalu berubah-ubah dan saling meniru pada awalnya. Ini menimbulkan kreativitas para perajin batik Pekalongan untuk selalu membuat motif batik baru.
Salah satu daya tarik utama batik pekalongan adalah keunikan motifnya. Corak dan motif yang dipergunakan mencakup berbagai elemen, seperti bunga, binatang, tokoh wayang, dan pola geometris. Desainnya yang indah dan rumit mencerminkan keahlian tangan para perajin batik motif Pekalongan.
Satu hal yang mencolok dari batik daerah ini adalah warna-warna yang dipakai dalam membatik yang membuatnya menarik perhatian. Penggunaan warna-warna yang cerah dan kontras memberi citra yang menawan.
Dari kisahnya, batik di sini menjadi lebih berkembang setelah ada pengusaha batik Belanda bernama Eliza Van Zuylen membangun workshop di wilayah tersebut. Berdasarkan arahan Eliza, ada motif-motif batik Pekalongan baru yang berhasil diciptakan oleh para perajin batik.

Eliza Van Zuylen dari catatan sejarahnya merupakan salah satu orang yang memiliki peran besar atas kemunculan motif-motif baru batik. Melalui tangannya, batik Pekalongan mampu menembus pangsa pasar Eropa.
Para pembeli batik Van Zuylen rata-rata memang para bangsawan Eropa. Eliza popular di Eropa dalam rentang waktu antara 1923 hingga akhir 1946.
Pengusaha ini sangat terkenal dengan produk batiknya yang dikenal kehalusan kainnya dengan motif batik tumbuh-tumbuhan. Hingga sampai saat ini batik seperti itu dikenal sebagai ciri khas batik motif Pekalongan, di samping motif Jlamprang.
Apa saja sesungguhnya motif-motif batik Pekalongan ini? Berikut ini beberapa ciri motif batik daerah sini.
Motif asli Pekalongan adalah motif Jlamprang, yaitu suatu motif semacam nitik yang tergolong motif batik geometris. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa motif ini merupakan suatu motif yang dikembangkan oleh pembatik keturunan Arab.
Motif batik jlamprang diyakini dan diakui oleh beberapa pengamat motif batik, sebagai motif asli Pekalongan. S.K. Sewan Santoso dalam bukunya Seni Kerajinan Batik Indonesia yang diterbitkan Balai Penelitian Batik dan Kerajinan , Lembaga Penelitian dan Pendidikan Industri, Departemen Perindustrian RI (1973), mengatakan bahwa motif Jlamprang di Pekalongan dipengaruhi oleh Islam.
Artinya, motif ini lahir dari perajin batik di daerah ini ada yang keturunan arab yang beragama Islam. Seperti diketahui, agama ini melarang menggambar binatang maupun manusia atau mahluk hidup lainnya dalam kain batik maupun lukisan. Ini membuat para perajin batik memiliki ide kreatif yaitu dengan membuat motif batik secara geometris dengan cara nitik pada motif batik jlamprang.
Namun ada pendapat berbeda. Pendapat berbeda ini menilai Jlamprang merupakan motif batik yang muncul karena pengaruh kebudayaan Hindu Syiwa.
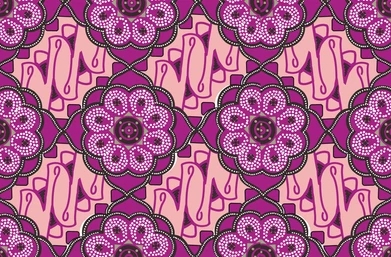
Dr. Kusnin Asa memiliki pendapat bahwa motif batik Jlamprang merupakan suatu bentuk motif yang kosmologis dengan mengedepankan satu pola ceplokan dalam bentuk lung-lungan juga bunga padma yang menunjukan sebuah makna mengenai peran dunia kosmis yang datang sejak agama Buddha dan Hindu berkembang di tanah Jawa.
Pola ceplokan pada motif yang distilisasi dalam bentuk yang lebih dekoratif menunjukan bahwa corak tersebut merupakan peninggalan dari masa prasejarah yang selanjutnya menjadi warisan agama Hindu juga Buddha.
Begitupun batik motif Pekalongan yang klasik sejatinya adalah motif semen. Motif ini hampir sama dengan motif klasik semen dari daerah Jawa Tengah lain, seperti Solo dan Yogyakarta.
Di dalam motif semen terdapat ornamen berbentuk tumbuhan dan garuda/sawat. Perbedaan antara batik di sini dan batik Solo atau Yogyakarta adalah pada produk Pekalongan klasik hampir tidak ada cecek. Pada batik klasik, semua pengisian motif berupa garis-garis.
Selain itu, beberapa kain batik yang diproduksi di Pekalongan mempunyai corak Cina. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ornamen Liong berupa naga besar berkaki dan burung Phoenix pada motif batiknya. Burung Phoenix merupakan sejenis burung yang bulu kepala dan sayapnya berjumbai, serta bulu ekor berjumbai juga bergelombang.
Kain batik pekalongan yang dikembangkan oleh pengusaha batik halus keturunan China kebanyakan memiliki motif berupa bentuk-bentuk realistis dan banyak menggunakan cecek-cecek, serta cecek sawut (titik dan garis).
Sementara itu, soal pewarnaan yang cerah, disebutkan bahwa penduduk daerah pantai menyukai warna-warna yang cerah seperti warna merah, kuning, biru, hijau, violet, dan orange. Sedangkan warna soga kain batik berasal dari pewarnaan tumbuhan.
agendaIndonesia
*****





















